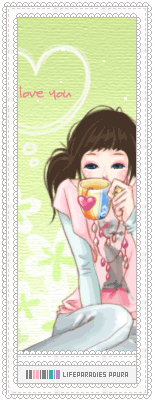Setiap malam ia selalu bermimpi kalau dirinya adalah seekor kelinci putih yang lucu, yang mampu melompat ke sana-ke mari di sebuah halaman pekarangan nan luas, dan memiliki seorang majikan perempuan nan baik hati yang selalu setia merawat dan menjaganya. Setiap malam pula ia selalu memanjatkan doa kepada yang maha kuasa agar keesokan paginya ia sudah memiliki telinga yang panjang, bulu putih yang halus menyerupai bola kapas, hidung mungil kemerahan, dan sorot mata yang memancarkan kanak-kanak.
Namun tempat ia berpijak bukanlah di sebuah halaman pekarangan nan luas, melainkan berkubang di lumpur kotor berwarna pekat kehitaman yang kerap menguarkan aroma busuk. Ia juga bukan seekor kelinci putih yang manis dengan kedua telinga yang panjang, hidung mungil kemerahan, dan sorot mata yang kekanak-kanakan. Ia hanya seekor katak buruk rupa yang setiap malamnya hanya bernyanyi dengan nada sumbang di dalam kubangan lumpur demi membunuh rasa sepi yang dipeluknya tiap malam.
Setiap sore saat senja menyepuhkan warna kemerahan di kaki langit, sang katak tidak pernah lupa untuk keluar dari kubangan lumpur guna melihat wajah seorang perempuan dengan seekor kelinci dari balik luar pagar pekarangan. Dengan saksama kedua bola mata bulatnya memerhatikan setiap detail bagian dimana saat perempuan itu menggendong kelinci berwarna putih dengan kedua tangan rampingnya. Ia juga memerhatikan dengan saksama bagaimana jemari lentik perempuan itu menyisir setiap bagian bulu kelinci dan membelainya dengan lembut penuh keanggunan.
Saat senja sudah hilang tak berbekas di kaki langit dan berganti dengan pekat malam, Sang katak bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke kubangan lumpur tempat tinggalnya guna menghindari serangan-serangan dari banyak ular yang gemar memangsa kaumnya bila malam sudah menjelang. Hal seperti ini terus dilakukan oleh sang katak sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kesehariannya tiap sore.
Sang Katak buruk rupa tidak tahu siapa nama sang perempuan dengan seekor kelincinya itu, namun di satu senja pernah saat ia memerhatikan sang perempuan sedang asyik bercakap-cakap dengan kelinci itu dari balik luar pagar pekarangan, ia mendengar suara seorang perempuan lain dari dalam rumah yang memanggil nama Perempuan itu dengan nada cukup keras. Nama itu kini terdengar begitu abadi bagi telinga sang katak, nama itu terdengar bertalu-talu di dalam pikirannya setiap hari, bahkan nama itu kini selalu ia nyanyikan dengan nada sumbang di dalam kubangan lumpur tiap malam. Nama itu adalah Alina.
Setiap sore sang katak selalu menanti kedatangan perempuan itu di halaman pekarangan belakang dengan harap-harap cemas, sementara sang katak bersembunyi di balik luar pagar pekarangan. Kepala mungil dan kedua bola matanya yang bulat sesekali mendongak dari sela-sela rerumputan. Di halaman pekarangan itu sudah menunggu sang kelinci berwarna putih yang acap kali melompat-lompat menjelajahi setiap sudut halaman pekarangan,mengendus-endus rerumputan yang kehijauan, sesekali sang kelinci masuk ke kandang guna mengunyah wortel dengan kedua giginya yang mungil sebelum kembali melompat-lompat.
Sang katak selalu mengartikan kalau setiap lompatan yang dilakukan oleh sang kelinci bisa jadi merupakan sebuah bentuk ekspresi kebahagiaan sang kelinci ketika menunggu sang majikan. Lama sang katak bersolilokui dari balik luar pagar halaman, sampai pada akhirnya pintu berwarna keputihan itu mengeluarkan suara deritan pertanda dibuka dari arah dalam. Seketika semua lamunan sang katak menjadi luluh lantak.
Ia melihat bagaimana sang perempuan dengan gelombang rambut kehitaman yang menyala tengah menghela langkah kaki dengan sedikit terburu-buru pertanda tak sabar untuk segera memeluk binatang kesayangannya. Sementara sang kelinci tidak ketinggalan melompat-lompat dengan lincah mendekati perempuan itu dan berakhir dengan jatuh dipelukan sang majikan. Kedua bola mata sang katak untuk kesekian kalinya tak jemu-jemu memandang pemandangan sang perempuan dengan seekor kelincinya hingga puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Dan ketika senja sudah mulai terlihat redup, dengan sigap ia kembali ke kubangan lumpur tempatnya bernaung.
Senyum sang perempuan selalu terbayang-bayang di tempurung kepala sang katak, Pikirannya ibarat sebuah film yang terus menerus memutar kejadian saat-saat dimana senyum sang Perempuan itu tengah merekah ketika sedang menggendong kelinci mungil miliknya, Pikirannya juga terus menerus memutar adegan dimana sang perempuan tengah mengelus-elus dengan lembut helai demi helai bulu sang kelinci. Pernah suatu malam sang katak bermimpi kalau mendadak ia menjadi sang kelinci mungil berbulu putih yang melompat-lompat di halaman pekarangan rumah.
Ia tengah menantikan kepulangan sang majikan, pintu berwarna keputihan itu terbuka dan sang perempuan beringsut memeluk dan menggendongnya dengan lembut. Ia dapat merasakan bagaimana jemari lentik sang perempuan itu membelai setiap helai bulu putih halusnya, ia juga dapat merasakan bagaimana telunjuk sang perempuan mengelus-ngelus hidungnya yang kemerahan dengan canda tawa. Sesaat kedua matanya menangkap gambar seekor katak yang sedang mengintip dari balik luar pagar pekarangan, sekejap kemudian raganya sontak berpindah dari kelinci yang sedang berada di pangkuan sang perempuan melesak masuk ke dalam raga katak buruk rupa yang tengah berada di balik luar pagar pekarangan. Dan mimpi itu adalah mimpi terburuk yang pernah dialami sang katak malam itu.
DI satu malam yang hening. Sang katak sedang menimbang-nimbang sebuah rencana kalau di satu senja ia akan masuk ke dalam halaman pekarangan tanpa sepengatahuan sang kelinci. Ia ingin sesekali menampakkan dirinya kepada sang perempuan, Ia tidak ingin terus-menerus hanya diam teronggok dari balik luar pagar pekarangan sementara kedua matanya tak henti-henti menatap keindahan sang perempuan. Setelah lama berpikir. Setelah lama menimbang-nimbang. Akhirnya Sang katak sampai kepada keputusan bahwa ia akan menampakkan dirinya kepada sang perempuan di halaman pekarangan esok sore.
Ia ingin merasakan bagaimana dirinya dapat dipeluk, digendong, dan dibelai oleh sang perempuan, sang katak merasakan bahwa dirinya juga layak dijadikan binatang peliharaan kesayangan kedua oleh sang perempuan, toh ia juga bisa melompat-lompat dengan lincah seperti yang dilakukan sang kelinci, bahkan bila sang perempuan telah resmi menjadikannya sebagai binatang kesayangan, sang perempuan tidak perlu repot-repot untuk memberinya makan dengan wortel , cah kakung, brokoli atau segala macam sayuran. Cukup letakkan saja dirinya di pekarangan, maka ia akan melahap semua nyamuk taman yang beterbangan guna menghidupi dirinya, ia juga tak perlu repot-repot dibuatkan kandang seperti sang kelinci, ia akan terjaga sepanjang malam untuk untuk sekadar mengumandangkan lagu-lagu cinta dengan suara sumbangnya. Lagu cinta tentang seekor katak yang jatuh hati dengan seorang anak perempuan manusia.
Senja sudah mulai menorehkan warna kemerahan di cakrawala. Meninggalkan siluet sejumlah burung-burung yang sedang terbang secara berombongan seraya membentuk formasi huruf “v”, sang katak dengan sigap keluar dari kubangan lumpur tempat dimana pikirannya sudah menghabiskan banyak energi untuk menimbang-nimbang dan memikirkan rencana besar ini. Namun bagaimanapun tekadnya sudah bulat, sore kali ini ia memutuskan untuk menampakkan dirinya kepada sang perempuan di halaman pekarangan.
Ia yakin bila ia melompat-lompat dengan lincah sama seperti yang dilakukan sang kelinci saat menjelang kedatangan sang perempuan, maka sang perempuan pastilah akan memeluk dirinya sama seperti sang perempuan memeluk sang kelinci. Bila ia melompat-lompat sembari beringsut mendekat kepada sang perempuan pastilah sang perempuan akan membuka lebar-lebar tangannya, lalu sang katak akan jatuh dalam pelukan sang perempuan, dan ia akan digendong, dibelai, oleh jemari-jemari indah sang perempuan, bahkan sang katak tidak sabar kalau sang perempuan akan memainkan hidung sang katak yang kehijauan dengan jari telunjuk mungilnya sama sebagaimana sang perempuan kerap menorehkan jari telunjuknya ke hidung kemerahan sang kelinci.
Kedua bola mata sang katak tengah memindai setiap sudut bagian pekarangan dari balik luar pagar pekarangan. Seperti biasa sang kelinci masih melompat-lompat dengan lincah kesana-kemari menjelajahi pekarangan. Disaat sang kelinci tengah berada jauh dari jangkauan tempatnya bersembunyi, dengan sigap sang katak melompat masuk melalui celah pagar besi yang cukup luas untuk dilalui oleh badannya yang kecil. Sang katak melompat dan melesak masuk ke dalam sebuah pot tanaman yang berada tepat di samping pintu berwarna keputihan itu. Cukup lama ia bersembunyi di dalam pot demi menunggu sang perempuan keluar dari balik pintu keputihan itu.
Tak sampai setengah jam, pintu berwarna keputihan itu pada akhirnya terbuka, menimbulkan derit suara yang menusuk telinga sang katak. Dengan cekatan sang katak memutuskan melompat keluar dari dalam pot dan melakukan lompatan-lompatan yang nyaris sama seperti yang dilakukan oleh sang kelinci saat kedatangan sang perempuan. Namun sial, di saat sang katak tengah melakukan lompatan-lompatan yang cukup tinggi, ternyata yang keluar dari pintu keputihan itu bukan sang perempuan yang selama ini ia kenal. Perempuan kali ini terlihat jauh lebih tua, gemuk, dan berperawakan seperti nenek sihir.
Sang perempuan tua itu pun secara spontan memekik bak orang kesurupan sembari menutup kembali pintu berwarna keputihan tersebut dengan teramat keras dan masuk kembali ke dalam. sementara sang katak menghentikan lompatannya. Ia cukup kaget mendengar suara perempuan tua itu. Ya, suara itu. Suara itu seperti suara yang selama ini ia dengar dari arah dalam pintu. Suara yang selalu memanggil nama sang perempuan dengan amat keras.
Sang katak masih menemukan sedikit harapan saat pintu keputihan tersebut kembali terbuka untuk kali keduanya, namun lagi-lagi perempuan tua, gemuk, dan berperawakan seperti nenek sihir itu yang menampakkan diri! hanya Kali ini kondisinya jauh lebih buruk dari sebelumnya, kali ini ia tengah membawa Sapu! Ya, sapu yang cukup panjang dengan ijuk yang cukup lebar pada ujungnya! Sang perempuan tua tersebut mengayunkan sapunya tepat ke arah sang katak berada dengan teramat keras?seperti ada niat untuk melumatkan sang katak seketika. Beruntung dengan insting yang cepat dan gerakan cukup tangkas sang katak berhasil menghindar dari serangan sapu tersebut dan segera melakukan lompatan yang cepat untuk keluar dari pekarangan. Sang katak pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke kubangan lumpur. Ia kembali dengan membawa hati yang tengah bermuram durja.
Senja esoknya, sang katak memutuskan untuk tidak menyerah akibat kejadian yang hampir membuatnya tewas di ujung sapu sang perempuan tua berparas nenek sihir itu. Kali ini ia meyakinkan dirinya kalau ia tidak akan mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Yah, tidak untuk kedua kali, sebab hanya keledai yang melakukan kesalahan lebih dari dua kali. Kali ini ia tidak akan keluar dari pot sebelum memastikan bahwa yang keluar dari pintu keputihan adalah sang perempuan yang amat dikaguminya itu, bukan seorang perempuan tua-gemuk berperawakan nenek sihir yang siap melumatnya dengan ujung sapu!
Untuk kedua kalinya sang katak merencanakan masuk ke halaman pekarangan, dan bersembunyi di pot yang berada tepat di samping pintu berwarna keputihan tersebut. Seperti hari kemarin, kali ini ia tidak mengalami kesulitan sama sekali untuk masuk ke halaman pekarangan melalu salah satu celah pagar. melompat melesak masuk ke dalam pot tanpa diketahui oleh sang kelinci yang sepertinya sedang asyik mengunyah wortel di dalam kandang. Di dalam pot yang rimbun dan sedikit lembab ia berusaha untuk menahan jantungnya yang hampir mencuat keluar. Entah karena rasa gugup atau rasa takut.
Selang tiga puluh menit kemudian, pintu berwarna keputihan itu terbuka dan menampakkan sang perempuan yang selama ini ia kagumi tengah menghela kaki ,beringsut mendekati sang kelinci. Sang katak tidak serta merta langsung melompat menghampiri sang perempuan, ia dengan kedua bola mata bulatnya dengan teliti memindai seluruh sudut ruang pekarangan?guna mencari tahu apakah perempuan tua berperawakan nenek sihir itu sedang berada di sekitar atau tidak. Setelah dirasanya aman.
Ia segera melompat dari dalam pot dan mendekati sang perempuan yang kini tengah duduk di tengah-tengah pekarangan bersama sang kelinci. Sang katak terus melompat dengan tinggi. Kedua bola matanya bersitatap dengan kedua bola mata sang perempuan yang teramat indah itu. Dan ah, itu dia senyum yang merekah itu mengembang dengan sempurna di wajah sang perempuan, mungkin sebagai pertanda kalau sang perempuan juga menyukai dirinya. Sang katak terus melompat dan melompat ke arah sang perempuan yang kini sudah mulai membuka kedua tangannya lebar-lebar. Ia melompat dan terus melompat. Jarak antara mereka sudah sedemikian dekat. Kedua tangan ramping milik sang perempuan sudah terasa semakin nyata di kedua bola matanya yang bulat, kali ini ia bahkan bisa mencium aroma sang perempuan yang dapat membiusnya dengan instan. Satu lompatan lagi maka ia akan mendarat di pelukan sang perempuan.
Dan pada akhirnya ia mendarat di pelukan sang perempuan dengan sempurna. Ia begitu amat senang, ia tidak percaya kalau impiannya selama ini untuk dekat dengan sang perempuan pada akhirnya dapat terwujudkan juga.
Sang perempuan meletakkan sang katak di dalam sebuah kotak kardus kecokelatan dengan lembut. Sang katak tidak tahu kenapa ia harus diletakkan dalam sebuah kardus kecokelatan, karena ia ingin bermain dengan sang perempuan, sama halnya seperti sang kelinci yang selalu setia menjadi teman bermain sang perempuan, ia pun merasa kalau ia dapat menjadi teman yang setia bagi sang perempuan.
Sang katak mengharapkan kalau dirinya juga akan dipeluk, dibelai, dan hidung mungilnya yang kehijauan akan ditorehkan oleh jari telunjuk sang perempuan. Namun pada kenyataannya sang perempuan malah pergi meninggalkannya sendiri di sebuah kardus kecokelatan. Sang katak terpekur dengan heran dan sedikit gelisah. Namun ia masih menaruh pada sedikit harapan kalau sebentar lagi sang perempuan akan kembali dan mengeluarkannya dari dalam kardus kecokelatan ini dan mengajaknya bermain di pekarangan.
Kedua bola matanya menari-nari setelah dilihat kembalinya sang perempuan, ia yakin dan teramat yakin kalau sang perempuan kini kembali untuk mengeluarkannya dari dalam kardus kecokelatan, dan berniat untuk menggendongnya, membelainya, dan memainkan hidung mungil kehijauannya dengan jari telunjuknya. Namun apa yang dilihat oleh sang katak begitu lain. Sesuatu yang dilihatnya kini teramat horor dan terasa mencekik lehernya. Sang perempuan yang dikaguminya itu kini terlihat membawa sapu dengan ujung ijuk yang cukup besar. Ya, sebuah sapu yang pernah digunakan oleh sang perempuan tua berperawakan nenek sihir yang kemarin untuk melumat dirinya.