

Pertama kali aku melihatnya di sebuah pameran lukisan tunggal di sebuah galeri di Cigadung Raya. Karena tak mengenal penulisnya, dan karena aku hanya datang atas undangan sorang teman, tak banyak yang bisa kunikmati selain memandangi wajah orang-orang.
Barangkali sama seperti aku yang sama sekali tak mengerti arti gambar-gambar yang diguratkan di atas kanvas, ia pun hanya celingukan. Wajahnya muram seperti kehilangan sesuatu, atau seseorang?
Lukisan, bagiku selalu mendatangkan aura sakit hati. Bukan, bukan karena aku pernah menjadi objek lukisan atau pernah dikhianati seorang pelukis. Alasan-alasan melankolis seperti itu sama sekali tidak ada dalam sejarah perjalanan cintaku. Barangkali karena dulu aku pernah terjebak di FSRD ITB namun tak jua menemukan apa yang kucari selain jemari yang belepotan cat air dan mabuk krayon, sekarang aku lebih menikmati mabuk kata-kata dan metafora; dunia kepenulisan.
Lelaki itu, memandangiku yang tengah berdiri di bawah sebuah lukisan abstrak dengan mulut menganga , ia tersenyum lalu mendekat. “Lukisan yang indah, bukan?” sapanya. “Barangkali iya,” bahuku bergedik. “Excuse me?” kedengarannya ia tak setuju. “Anda bertanya pada mata orang awam. Saya hanya bisa menikmati gradasi warna dan mengagumi bagaimana semua cat air itu ditumpahkan di atas kanvas tanpa bisa memahami apa maknanya. Jadi, barangkali lukisan ini memang indah, tapi saya tak pernah tahu bedanya bukan?” “Apa saya pernah melihat Anda sebelum ini?” mulailah ia berbasa-basi.
Aku meneliti wajahnya. Muram, meski seutas senyum bertali di bibirnya. “Tidak,” jawabku tanpa menggelengkan kepala. Aku tak yakin, rongga hatiku bersuara. “Ah, sayang sekali. Padahal sejak tadi saya merasa kalau kita pernah dekat di kehidupan lampau,” nadanya kecewa yang tak dibuat-dibuat. “Barangkali di kehidupan lampau saya ini setangkai anggrek bulan dan Anda adalah pot tanah liatnya,” kuharap ia tahu bahwa aku sedang bercanda. Tapi ia termenung sebentar, lalu katanya. “Tidak, lebih dekat daripada itu.” “Bagaimana kalau mawar dengan durinya? Anda yang mawar, saya yang duri,” tawarku, masih dengan kelakar.
Ia seperti tak sadar bahwa konsep reinkarnasi yang ditawarkannya adalah omong kosong bagiku. Mati satu kali, hidup pun cukup satu kali. “Saya masih yakin bahwa dulu kita sepasang kekasih,” ia bertutur pelan. Jemarinya meremas pamflet yang tadi dibagikan di pintu masuk. Mataku terpaku pada jemarinya. Satu, dua, tiga, empat, tiba-tiba otakku menghitung. Jemarinya hanya berjumlah enam. Tiga di kiri, tiga di kanan. Keduanya tanpa jari manis dan kelingking. “Cacat sejak lahir,” jelasnya tanpa kuminta. “Ah, saya kira saya tak perlu minta maaf kalau begitu? Tapi sungguh, saya tak bermaksud lancang.”
Matanya yang sipit kian menyipit ketika ia tertawa. “Ibu-ibu jaman dulu selalu kurang gizi,” katanya di sela tawa. “Katanya beliau kekurangan asam folat ketika mengandung saya,” ia mengacungkan kedua tangannya. Aku hanya tersenyum, mengangguk. “Tapi saya harus minta maaf atas kata-kata saya tadi. Mmmhh… mengenai kita sebagai sepasang kekasih di kehidupan lampau. Meski saya memang tak berbohong tentang itu.” “Itu kan hanya dejavu-nya Anda. Saya tak percaya dengan reinkarnasi dan semacamnya.” “Anda penulis?” tanyanya. Aku terdiam sebentar. “Iya,” jawabku singkat. “Kekasih saya itu juga seorang penulis,” matanya mengawang merayapi dinding-dinding galeri. Ada kepedihan dan kesepian yang tak bisa dilukiskan oleh cat air sebanyak apapun. Tubuhku seketika tersedot ke dalam pusaran kabut, mendarat di sebuah maze labirin tak berujung. Aku tak bisa keluar; terperangkap di dalam matanya.
Ketika kabut tersingkap, aku tengah berada di sebuah ranjang rumah sakit. Bau obat, selang-selang berseliweran berujung jarum dirajamkan di tanganku, tabung oksigen, dan segala macam alat medis yang lampunya berkerlap-kerlip.
Lelaki itu, duduk di samping ranjang, menggenggam sebuah buku tebal yang kukira Al-Quran atau bibel. Tapi ternyata itu sebuah buku puisi.
Matanya muram berpendar, berkaca, bersungai. Aliran deras dari matanya menitik satu demi satu lalu kian deras seiring suara bip bip dan lantunan isak. Manusia manapun akan terenyuh melihat pemandangan itu. Setiap orang, kecuali mungkin aku.
Mata perempuan yang tengah berbaring itu terpejam, keseluruhan wajahnya diam. Namun tak dapat disangkal bahwa wajahnya, setiap guratannya, adalah replika wajahku. Dan aku, tiba-tiba sudah berdiri di ujung ranjang, memandangi mereka berdua, tapi tak jua menemukan korelasi antara perempuan yang persis diriku dan lelaki yang mengaku kekasihku itu.
Pelan-pelan, kabut turun kembali. Mula-mula tipis lalu bergumul-gumul menutupi setiap partikel udara. Terasa menyesakkan. Aku kembali berada di galeri, limbung dan nyaris pingsan. “Anda baik-baik saja?” ia menahan tubuhku.
Suaranya bagai gema yang jauh ketika aku dibimbingnya duduk di bangku teras, keluar dari galeri yang mulai penuh. “Apa itu tadi?” nafasku memburu. “Apanya yang apa?” ia bertanya balik dengan nada bingung. “Saya… siapa nama kekasih Anda?” pertanyaanku berganti. “Ishtar,” tukasnya. “Anda pasti bercanda,” aku mulai panik. “Tidak, saya serius.”
Kurogoh dompet dan mengangsurkan KTP, ia menyambutnya tanpa berkata apa-apa. Matanya menelusuri setiap huruf yang tercetak di sana. “Ah, bahkan Anda dan dia punya nama yang sama,” gumamnya, sedikit gembira. “Lalu apa yang terjadi dengannya?” “Saya lupa. Sudah saya bilang kalau itu terjadi di kehidupan yang lalu, bukan?” “Ide Anda itu terlalu utopis,” aku kesal dan beranjak. “Ishtar!” panggilnya.
Aku diam sejenak tanpa menoleh. “Bagaimana kalau itu terjadi di masa yang akan datang?” ia mengejarku. “Dan berakhir koma di rumah sakit? Tidak, terima kasih,” aku mulai berjalan.
Namun, sebelum aku terlalu jauh, kabut kembali turun. Tidak lagi tipis melainkan bergerombol, mendesakku, memboyong tubuhku kembali ke dalam labirin hitam pekat. Dingin dan gigil. Aku berteriak minta tolong, tapi suaraku ditelan bisu. Galeri menghilang. Lukisan-lukisan menghilang. Orang-orang menghilang. Yang ada hanya mata lelaki itu. Dan kabut. * Bandung, 14 Agustus 2010 Setelah membaca kumcer Cecep Syamsul Hari













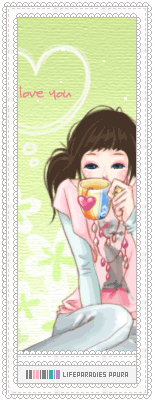
0 komentar:
Posting Komentar