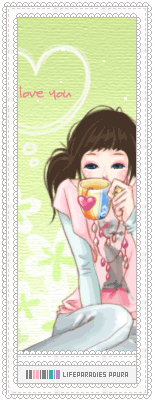Orang memanggil bapak tua itu dengan panggilan Pak Dol. Badannya tinggi besar, kulitnya hitam legam, dan mukanya gemuk sembab. Sejak lima belas tahun yang lalu dia hidup sendiri di rumah papan itu. Rumah papan yang selalu berserakkan dengan puntung rokok di mana-mana, peralatan masak dan macam-macam bungkus bumbu masakan menjadi saksi kesendiriannya. Bapak tua itu memang senang memasak.
Dari jendela ruang tamu yang hanya berisi satu bangku, Bapak tua duduk menatap lurus ke depan. Tatapannya kosong. Sejenak kemudian tatapannya menghambur ke setiap rumah tetangga. Bola matanya mampir pada Ibu tua di depan rumahnya dengan kebaya lusuh dan selendang usang, duduk di depan pintu bersama anak gadisnya sambil berbincang. Bapak tua tersenyum kecil melihatnya. Matanya berkaca-kaca. Ada kerinduan di sana.
Terdengar alunan lagu lantunan tape dari rumah tetangga dengan lirik pantun Minang yang menggelitik: Kalaupun ada batang cumanak. Daunnya banyak yang muda. Kalaupun ada banyak dunsanak. Tapi tak ada tempat beria.
Yah, mereka jauh. Nasib telah memisahkan bapak tua dengan anak istrinya. Keluarga bapak tua masih hidup. Terutama istrinya yang sama sekali belum diceraikannya.
Bapak tua menyalakan sebatang kretek dan menghisapnya. Dia seolah lupa dengan penyakit yang ada di tubuhnya. Saat dihisap, percikan api rokok melompat. Dengan reflek matanya menyipit. Sesaat kemudian perhatiannya beralih pada sebuah foto keluarga dengan bingkai yang lumayan besar di sisi dinding. Dia mengamati foto keluarga yang dulu sangat harmonis. Foto yang telah kusam, dua puluh tahun yang lalu. Saat itu Zainal, anak sulungnya masih berumur tiga belas tahun, yang bungsu masih SD kelas satu. Bapak tua menghela nafas.
saat ini usianya sudah enam puluh lima tahun. Harusnya di masa tua dia berkumpul dengan anak dan istrinya. Kalau sakit dia tidak perlu memanggil Buyung, anak tanggung di sebelah rumah yang selalu ada di saat dia butuh pertolongan. Sesekali Buyung juga yang membersihkan rumahnya.
Rumah papan yang berisi sebuah kompor minyak dan beberapa alat masak di dapur, tv tujuh belas inci, kipas angin, dan kasur tipis di kamarnya. Sebuah bangku di ruang tamu. Seraya menghisap rokok, bapak tua menatap ke jalan. Anak-anak bermain lumpur, berlempar-lemparan tanah. Ada yang mengejar layang-layang putus.
Waktu pun menyergapnya. Kenangan masa lampau. Ketika anak-anaknya mengantarkan kawa untuknya, ke sawah. Berjalan di pematang. Seraya tertawa-tawa mereka akan berebutan menangkap capung-capung merah dan belalang. Kemudian mereka makan bersama-sama bapak tua. Dengan samba lado dan ikan asin yang dibuat istrinya di rumah.
Yah, kenangan! “Itu memang salahku.” Bapak tua itu bergumam. Pandangannya menerawang ke masa lalu.
Lima belas tahun yang lalu anak-anaknya dia suruh ke Medan untuk sekolah. Saat itu si Zainal akan masuk Kedokteran, anak keduanya si Ani kelas satu SMA, anak ketiganya si Upik kelas dua SMP, dan anak bungsunya si Rustam kelas empat SD. Pikirnya, lebih baik sekalian saja keempat anaknya sekolah di sana. Pendidikan di sana lebih berkualitas. Dia ingin anak-anaknya sukses. Mereka pindah bersama istrinya. Di Medan, bapak tua sudah lama mempunyai rumah. Bahkan rumah di Medan besar dan mewah, tidak seperti rumah papan yang ditempatinya. Sekarang anak-anaknya sudah berkawinan.
“Melamun, Pak Dol?” Seorang tetangga yang melewati rumahnya, menyapa. Dia hanya tersenyum kecil. Kemudian bayang masa lalu kembali hadir. “Tak ada gunanya tanah pusaka yang banyak menghasilkan seperti kelapa, padi, jagung dan sebagainya,” suaranya berbisik, lalu menarik napas.
Dia melempar puntung rokoknya yang sudah memendek ke sembarang arah. Kalau ada bensin atau minyak lampu tumpah, rumah itu pasti sudah terbakar.
Anaknya si Zainal, berhenti kuliah di tengah jalan dengan alasan tidak sanggup menghadapi pelajaran Kedokteran. Padahal saat sekolah dulu prestasinya sangat baik. Kemudian didengarnya sudah menikah karena anak gadis orang sudah hamil dua bulan dibuatnya.
Anaknya si Ani, setelah tamat SMA tidak lanjut kuliah karena tidak ingin masuk jurusan Hukum seperti yang diinginkan bapak tua. Dia lebih memilih menikah muda.
Anaknya si Upik saat SMA kelas dua berhenti sekolah karena terlibat hutang di mana-mana. Anak itu memang sangat boros. Lagaknya seperti anak pejabat saja! Dia lari dari Medan ke Kutacane, dan sampai sana menikah di bawah tangan.
Si bungsu Rustam tidak tahu kabarnya sekarang. Terakhir kali Rustam masih SMP. Sejak berita terakhir yang bapak tua dengar tentang Upik, dia syok berat dan tidak mau menghubungi mereka lagi. Telepon selulernya dia jual agar tidak dihubungi. Sejak itu pula dia divonis sakit jantung dan paru-paru.
Sebagian menyalahkannya karena tidak mengawasi mereka di Medan. Istrinya tak bisa mendidik anak-anak seorang diri. Istrinya tidak tegas dan keras sepertinya. Bapak tua sebagai kepala rumah tangga yang harusnya memimpin. Anak-anak juga butuh perhatian darinya, bukan cuma materi. Bapak tua kembali menarik nafas panjang. “Mereka pikir menikah itu gampang.” Dia tersenyum getir. “Apalagi pendidikan mereka tidak tinggi. Kerja apa si Zainal untuk anak dan istrinya? Ani dan Upik juga. Apa mereka pikir dengan mengharap dari suami saja cukup?” Bapak tua menggeleng lemah, tersirat kekhawatiran di wajahnya. “Pikiran mereka terlalu singkat.”
Sejenak kemudian dia menggeleng lagi, kali ini cepat. “Tidak! Mereka benar. Ini memang salahku. Istriku tidak pernah salah. Walaupun aku sempat menyalahkan istriku karena tidak pandai mengurus anak.” Dia masih bergumam dalam kesendirian.
Sebuah jam lama di dinding rumahnya menunjukkan pukul enam petang. Bapak tua bangkit dari duduknya. Tertatih menuju almanak yang tergantung di dinding. Matanya tak lepas dari angka-angka tersebut. Seminggu lagi bulan puasa. Tahun ini dia harus melewati lebaran sendiri lagi. Dia rindu sama anak dan istrinya. Padahal dulu dia sangat mencintai istrinya. Istrinya sangat cantik dan saleha. Tidak pernah membantah suami. Ini semua karena kekerasan hatinya. Dia sangat kecewa dan sakit hati karena anak-anaknya tidak ada yang sukses sesuai dengan keinginannya. Hari sudah senja. Di ujung, Gunung Sago terhampar jelas. Dia segera menutup jendela dan pintu. * Seminggu lagi lebaran. Bapak tua sudah sibuk menyuruh Buyung untuk belanja ke pasar, membeli bahan masakan untuk lebaran. Dia biasa memasak sendiri.
“Ungku akan memasak samba lado tanak, makanan kesukaan Pak Etek Zainal. Rendang kesukaan Etek Ani, pangek ikan kesukaan Etek Upik, dan kesukaan Apak Rustam kolak campur lemang.” Setiap lebaran, bapak tua mengurai makanan kesukaan anak-anaknya. Lalu dia akan memasaknya sendiri. Buyung hanya menolong memotong atau menggiling bahan yang dibutuhkan. Dengan memasak masakan kesukaan anak-anaknya setiap lebaran, bapak tua seolah merasakan kehadiran mereka.
Suara takbir bersahut-sahutan. Anak-anak berlarian dengan pakaian baru mereka. Berbondong-bondong keluarga menuju mesjid untuk shalat Ied. Ada juga yang datang jauh dari kota ingin berlebaran bersama orang tuanya yang sudah renta.
Dia Rijal, abang Buyung yang sudah sukses dengan gelar Dokter. Bapak tua melamun melihat mereka di depan pintu, kemudian berlinang air matanya. Dia sangat ingin anaknya sukses seperti Rijal walau hanya satu orang.
“Bapak,” suara panggilan anak muda di depannya mengejutkannya. Dia seperti mengenal wajah anak muda yang berdasi itu.
Anak muda itu mencium tangan bapak tua, lalu memeluknya erat. Bapak tua masih terpaku. “Kamu Rustam?” tanyanya antara percaya dan tidak. “Iya, Pak. Sekarang Rustam sudah jadi direktur di suatu perusahaan yang ada di Medan. Kami rindu sama Bapak.” Rustam mencium tangan bapaknya.
Air mata kebahagian mengalir di wajah bapak tua. Seorang wanita renta dituntun gadis tanggung keluar dari Honda jazz. Wanita renta itu adalah istrinya. Mereka menghampiri bapak tua. “Ini Ratih cucu kita, anak si Zainal,” kata si istri, lalu mencium tangan bapak tua.
Mata bapak tua berbinar pada istrinya, lalu menatap Ratih yang juga menyalaminya. Beberapa saat kemudian keluar lagi beberapa orang dari mobil, kemudian datang lagi satu mobil di belakang Honda jazz. Ketiga anaknya dan cucunya yang lain. Seketika sakit hati bapak tua hilang.