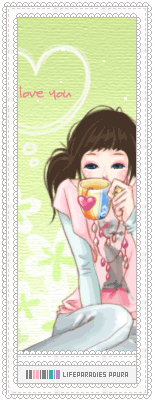Teriakanku semakin kencang, karena tiba-tiba bunyi guntur menggelegar, dan di sela suara tak berirama itu aku mendengar suara lain memanggil namaku ...
Teriakanku semakin kencang, karena tiba-tiba bunyi guntur menggelegar, dan di sela suara tak berirama itu aku mendengar suara lain memanggil namaku ... Perjalanan jauh dengan misi yang tak pasti memang jauh dari kesan menyenangkan. Buruk, tak punya gambaran yang jelas tentang apa yang akan terjadi. Sehingga tak ada sedikitpun kesempatan berkhayal tentang kemungkinan yang tak pasti sekali pun. Dengan sangat terpaksa harus diam, mulut tak bergerak dan pikiran dibiarkan mati. Proses kreatif yang menstimulus ekspresi air muka juga tak tercipta. Kaku. Badan bergerak tapi bukan karena perintah otak, hanya mengikuti gerak kapal yang berusaha bergerak konstan melawan hantaman gelombang Desember.
“Dari tadi tadi aku perhatiin, pandangannya koq kosong bang,” datang suara dari meja di sampingku. Aku di bar kapal. Sejenak menoleh ke arah datang suara, lalu kembali melihat kosong sambil bergumam, “Iya, lagi pingin sendiri.” Usai bergumam, aku sadar bahwa baru saja bercerita dan tidak menjawab pertanyaan. Lalu tidak ada suara lagi yang aku dengar. Aku mati suri, mungkin. Atau bahkan sudah mati duduk. Aku belum pernah mati. Tapi pengalaman seperti saat ini juga belum pernah kualami, sehingga aku berpikir mungkin sudah mati.
Tak sadar, aku sudah di geladak kapal. Menghadap ke lautan yang tidak biru tapi hitam. Sekarang malam. Angin malam menerpa keras dan kasar. Sweater hitam yang kupakai sepertinya memang tidak cocok menahan angin sekuat ini, sehingga dingin tetap menembus kulit meski tak sampai ke tulang. “Hai….”
Entah darimana datangnya, gadis yang tadi tahu pandangan kosongku di bar kapal, kini ada tepat di sampingku di geladak. Kami hanya berdua, tapi dia tampaknya lebih siap berada di sini daripada aku. Jaket kain ala Eropa dengan krah bulu angsa, membungkus tubuhnya sampai ke betis, sehingga sulit untukku menebak rampingkah dia? Atau montok?
Entahlah, mungkin dia gemuk sehingga memilih menutup kegemukannya dengan jaket besar dan panjang. Saya bisa memaklumi itu, soalnya dia sepertinya tipe gadis modern yang ingin tampil ramping tapi tak cukup kuat menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Namun yang pasti, dia tidak lebih tinggi dari aku. Ujung tertinggi topi dingin yang bertengger angkuh di kepala sejajar dengan telingaku saat kami sama berdiri tegak.
Gadis itu memang lebih siap ada di geladak daripada aku. Buktinya, dia pake topi dingin sedang aku hanya berharap pada rambut keritingku yang kubiarkan tebal. Kribo. Sama sekali tidak siap, karena tidak ada rencana untuk bersantai di geladak pada jam setengah dua belas malam.
Penumpang lain sudah lelap, sebagian bermimpi tentang liburan nan mewah di Nusa Dua. Kapal kami baru saja meninggalkan Benoa untuk terus ke Perak Surabaya. Aku belum tidur. Gadis di sampingku juga belum. Karena kalau dia tidur, dia pasti tidak di geladak, tetapi di kamarnya. Dia pasti sewa kamar di kapal ini. Jaketnya malam itu menjelaskan kalau kondisi ekonominya tidak sama dengan yang ada di dek ekonomi.
“Hai….” “Hai juga, belum tidur?” “Belum, kamu sendiri?’ Gadis ini, sekarang dia berani ber-kamu, padahal seingatku di sewaktu di bar tadi dia ber-abang. Mungkin dia sudah bisa menebak kalau usiaku tak jauh beda dengannya sehingga tidak perlu bersantun-ria. Atau dia ingin membangun suasana yang akrab. Kami di geladak kapal. “Sama,” jawabku sambil terus cerita jujur. “Akhir-akhir ini aku emang nggak bisa tidur. Sudah lebih seminggu” “Koq bisa,…. Kamu insomnia ya?” “Nggak, aku cuma takut gelap. Tiap aku coba terpejam, rasanya seperti dalam peti mati. Selalu ada mimpi buruk dalam tidurku” “Gimana rasanya?” “Dalam peti mati?” “Bukan,…” ia tersenyum. Mungkin pertanyaanku baginya terdengar lucu atau atau agak naif. Lalu menyambung, “Kamu kan sudah seminggu lebih nggak bisa tidur. Gimana rasanya tidak tidur selama itu?” “Can’t be explain. Tapi sepertinya aku harus tidur sekarang. Mudah-mudahan bisa. Selamat malam,” kataku sambil melangkah menjauh meninggalkannya di geladak. Aku mulai merasa kurang nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan gadis itu. Aku kurang siap menjawab. Karena menjawab berarti harus bercerita tentang persoalan yang sedang aku bawa. Padahal aku belum siap bercerita. Apalagi sekarang kantuk mulai menyerang. “Hei…!” kudengar ia setengah berteriak. “Kita kan belum sempat kenalan.” “Aku Silver. Silver Yohanes,” sahutku tetap melangkah. “Aku Helena. Helena Puji Astuti. Tapi panggil aku Helen,” sahutnya seolah pasti kalau kami akan ketemu lagi.
Kami berpisah di tempat itu, di geladak kapal. Jam setengah dua belas lebih tujuh belas menit. Aku ke dek tiga. Kulihat tempatku belum terisi. Aku tidur. Samping kiriku seorang Ibu muda tidur memeluk putri kecilnya. Keduanya lelap, terdengar dengkuran halus sekali, semakin halus, sampai aku tak mendengar apa-apa lagi. Aneh, aku bisa tidur dan baru terbangun saat terdengar pengumuman kapal akan segera sandar di Pelabuhan Perak. Hampir jam empat pagi. Luar biasa! Bukan karena obat tidur, tapi karena karena obrolan tak sampai seperempat jam dengan gadis bernama Helen, aku bisa lelap. Tak ada mimpi buruk. Andai aku bertemu dia dua Minggu sebelumnya, mungkin mataku tak akan cekung. Banyak hal yang bisa dijelaskan tapi akal sehat tidak cukup luas untuk bisa menerimanya sebagai hal yang rasional.
Sauh sudah dibuang, kapal Dobon Solo yang membawaku dari Dermaga Pilemon Labuan Bajo kini benar-benar berhenti di Pelabuhan Perak Surabaya. Aku sendiri sudah di luar kapal, agak jauh ke darat sibuk menawar angguna untuk mengantarku ke Perumahan Wisma Tropodo di Sidoarjo. Temanku menunggu di sana, di rumah kontrakan yang akan kami tempati berdua. Aku pilih angguna, uangku tak cukup untuk taksi. Tak banyak yang terjadi sepanjang perjalanan. Sopir Angguna sekitar empat puluh tahun bahkan tidak pernah bicara.
Jam 07.00 waktu Sidoarjo Di dalam kamar sebuah rumah mungil di jalan Dokter Sutomo, kompleks perumahan Wisma Tropodo. Rumah itu kontrakan temanku. Anak Solo bernama Bontos, bertubuh tambun, teman kampusku yang sekarang kerja entah sebagai apa di kawasan Rungkut. Saat aku datang dini hari tadi rumahnya terlihat bagus. Rapi.
Tetapi sepertinya sekarang ada yang berubah. Bontos tak ada di rumahnya. Malah kini terlihat ada beberapa perempuan berpakaian putih-putih. Mereka membelakangiku, bernyanyi tanpa syair. Tapi lagu itu, lagu yang mereka nyanyikan sepertinya sangat akrab di telingaku. Aku berpikir keras. Sangat keras sampai akhirnya aku sadar kalau lagu itu adalah salah satu lagu yang kukagumi. Mereka sedang bernyayi Ave Maria karya Schubert, bukan bernyanyi tetapi bersenandung. Aku ikut bersenandung sampai mereka menoleh dan menatapku. Oh, ada Helen di antara rombongan itu. Yang lainnya adalah perempuan-perempuan di sekitar hidupku. Tapi mengapa mereka bersama Helen?
Bukankah mereka sudah mati? Wajah dan tatapan bola mata mereka memerah. Aku sadar itu bukan tatapan persahabatan. Aku mencoba tersenyum. Tak ada balasan. Aku diam, tetapi mereka tetap melihatku. Dan,… Oh Tuhan, kini mereka mendekat. Aku melangkah mundur. Ketakutan. Aku takut sekali. Bagaimana mungkin orang berpakaian putih berjalan ke arahku dengan mata merah; dan… ya ampun di tangan mereka kini ada pisau belati mengkilap oleh cahaya yang datangnya entah dari mana. Aku heran dan sempat berpikir, bukankah dalam situasi seperti itu mereka seharusnya berpakaian hitam dan bernyanyi lagu mistis? Sehingga saya tidak usah ikut bernyanyi, dan langsung menjauh?
Aku takut, lari dan kali ini berteriak. Mencoba keluar dari rumah temanku. Teriakanku semakin kencang, karena tiba-tiba bunyi guntur menggelegar, dan di sela suara tak berirama itu aku mendengar suara lain memanggil namaku. Bukan suara perempuan yang bersenandung, tapi suara pria yang setengah teriak, putus asa. Sil..…… Silver……. Oh tidak, kenapa pria itu? Siapa dia? Teman Bontoskah? Tapi kenapa jadi begini? Aku terus berlari, tetapi gelegar semakin jelas terdengar. Namaku tetap disebut, dan aneh mereka, rombongan perempuan itu tetap bersenandung Ave Maria, sedang pria itu tetap memanggil namaku. Kini giliranku yang putus asa. Pasrah, sambil berharap mudah-mudahan mereka bukan malaikat maut.
Dan… Aku terbangun. Terima kasih Tuhan, tadi itu hanya mimpi. Tapi kenapa senandung Ave Maria itu masih terdengar? Kali ini lebih jelas. Dan bunyi guntur itu…….. Kepalaku bergerak liar. Menoleh ke arah meja di kamar kecilku, lalu berpaling ke pintu, lalu tersenyum. Aku tadi bermimpi, tapi sekarang tidak. Lagu Ave Maria Schubert masih tetap terdengar, tapi itu dari telepon selulerku. Alarm-nya memang Ave Maria. Berarti sekarang jam 7 pagi. Bunyi guntur ada, tetapi itu gedoran pintu di kamarku. Lalu ada yang memanggil.
Sil….. Silver…….ada apa? Itu suara temanku. Dia rupanya membangunkan aku. “Santai Tos, aku cuma mimpi buruk. Mungkin karena lama gak sempat istirahat,” jawabku. “Aku emang biasa gitu, mimpinya pasti aneh-aneh kalau udah kelelahan. Trus, kamu gedor-gedor pintuku ada apa?” tanyaku sambil merapikan tempat tidurku. “Ada telfon. Dari temanmu, cewek. Namanya Helen.” “Helen?” “Iya, buruan udah ditunggu lama,” suruhnya dan berlalu. Dia harus kerja. Aku tersentak, terburu-buru menuju pesawat telefon di pojok ruang tamu. “Halo,…..”
Sial, Helen tak cukup bersabar. Sapaanku dibalas dengan dengungan panjang. Telepon teputus. “Tapi apa benar itu Helen?” kata hatiku. “Lalu dari mana dia tahu nomor telfon kontrakan temanku?”
Aku terus mencoba mengingat-ingat, apa pernah aku berikan alamat Bontos ke orang lain. Tetapi semakin aku keras mencoba mengingat, semakin aku yakin tak mungkin seceroboh itu. Aku tidak pernah membocorkan alamat ini ke orang lain. Misi perjalananku dari Manggarai terlalu rahasia untuk dibicarakan dengan banyak orang. Hanya aku, dan beberapa gelintir orang dekatku yang tahu. Dan aku berani pastikan, tak satupun dari mereka yang kenal Helen, Jadi kalau toh yang telfon tadi adalah Helen, maka dia pasti tahu nomor itu bukan dari mereka.
Kriiiiiiiiiiing… kriiiiiiiiiiing,…
Telepon di sudut ruang tamu berdering. Aku ke sana, mendekat tapi ragu. Kuangkatkah telfon itu? Tapi otakku terlambat mengambil keputusan, karena di saat yang sama tanganku sudah bergerak dan… “Halo selamat pagi.” “Pagi Silver, baru bangun ya…” suara renyah terdengar bersih di gagang telfonku. “Kk.. kamu Helen?” “Iya…, kaget ya?” “Lumayan.” “Kamu pasti bingung dari mana aku tahu nomor ini kan?” “Eh… ii.. iya.” “Gini, pas kita lagi di bar kapal, ada kertas kecil jatuh dari saku belakang jins kamu. Tapi kamu ternyata nggak sadar. Waktu itu aku pikir kamu sedang bingung dengan sikapku yang tiba-tiba ramah padahal kita belum kenalan. Trus, waktu aku mau balikin tu kertas, eh kamu malah ke geladak. Ya udah, aku ikutin aja kamu ke geladak. Tapinya lagi, kamu keliatan nggak betah ngomong ama aku. Nggak jadi deh aku balikin tu kertas.” “Trus…? kataku sambil mencoba mengingat-ingat apa isi kertas itu. Sayang, sampai Helen nyerocos lagi aku belum juga bisa ingat isi kertas yang membuat gadis itu tahu nomor telfon temanku Bontos. “Teruus, kertasnya aku buka aja. Eh gak taunya cuma nomor telfon dengan tulisan kecil yang membingungkan. Kamu ingat kan?” “I…iya, sekarang aku ingat,” sahutku dengan nada bergetar. “Tempatku Bersembunyi Dari Kematian” aku bergumam melafalkan kembali tulisan yang aku buat pada kertas kecil berisi nomor telfon Bontos.
Aku memang sedang dalam perjalanan tanpa misi yang jelas. Aku cuma ingin lari dari kepedihan bertubi yang menimpaku akibat kematian orang-orang dekatku. Pertama kakak perempuanku, meninggal akibat kanker payudara ganas. Tak lama berselang, giliran istri pamanku meninggal saat melahirkan, ditolong dukun beranak. Lalu satu persatu wajah-wajah terkasih pergi dan tak pernah kembali. Sampai suatu saat, kematian itu hampir menjemputku. Aku takut, takut sekali pada kematian, juga takut mengetahui dan menyaksikan orang-orang di sekitarku mati. Aku lalu menghindar. Jauh dari peristiwa menyedihkan itu, dan kini di kontrakan temanku sedang menerima telepon.
“Nah itu dia,” datang suara dari seberang telfon. “Tulisan kamu jelas bikin aku bingung. Tapi yang bikin aku penasaran adalah, karena kita sepertinya sama. Sama-sama takut mati.” “Memangnya kamu…” “Iya,… aku memang sedang berusaha menghindar dari kematian. Makanya, karena kita sepertinya senasib, kita sebaiknya ketemu kan?” “Boleh, tapi untuk apa?” tanyaku tolol. “Biar kita bisa jadi teman. Kali aja, kalau dua orang yang menghindar dari kematian itu bisa berteman, maka kematian akan takut menghampiri. Kamu mau kan, Sil? Atau jangan-jangan kamu ada acara hari ini.” “Enggak koq, kebetulan aku gak ada acara. Kalo gitu, kita ketemu di Food Center Tunjungan Plasa jam 10, OK?”
Jam 09.33 Waktu Sidoarjo Aku baru selesai dandan, ketika telfon di ruang tamu berdering. Sial, padahal aku sudah siap-siap ke Tunjungan Plasa. Bertemu Helen, sambil nikmati dunkin donuts. “Halo.” “Silv, ini Bontos!” suara dari ujung telfon. “Ada apa, Tos?” “Aku di kantor polisi sekarang. Tadi mobilku dipinjem temen kantorku. Trus, pas di sekitar Tunjungan, temenku nabrak satu perempuan yang mau nyebrang.” “Lalu?” tanyaku tolol. “Ya, aku sepertinya gak bisa pulang sekarang. Urusannya masih lama sampai mobil aku keluar. Jadi kalo laper, kamu bisa cari sendiri kan. Warung di ujung gang itu langgananku. Udah ya…” “Eit entar dulu, Tos…” “Ada apa lagi toh..?” “Kamu tau gak nasib dan nama korban,” tanyaku ragu. “Emang kenapa?” “Ngng ... Nggak apa-apa kog, tapi perasaanku agak aneh aja.” “O…, kata Polisi sih korbannya langsung meninggal di lokasi kejadian. Namanya Helena Puji Astuti. Udah ya!” Sambungan telpon terputus. Gagang telfon masih dalam genggaman. Mendadak dunia di sekitarku berputar kencang. Temaram lalu gelap. Entah berapa lama aku pingsan. Saat bangun, tak ada yang berubah di sekitarku. Juga kenyataan bahwa kematian tak pernah jauh dari sisiku.