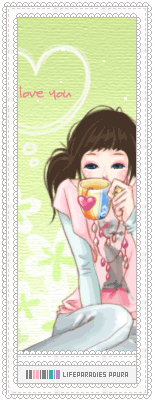Sebulan mereka bertemu. Oh tidak, mereka tetap bertemu sekarang, hanya saja waktu sebulan adalah hitungan ketika dia membangun mimpinya dengan penuh harap.
Hari itu di taman kota tak berpengunjung, dia duduk di kursi tembok tak terawat dan berdebu. Pemuda itu sedang bercerita dengan setengah suara, tentang kisahnya yang terakhir. Lebih tepat tentang kisah sekarang yang dia ingin jadi kisahnya yang terakhir. Telah banyak kata yang terucap, rangkaian kalimat yang bertutur jujur tentang jalan hidupnya pada rel yang dia sebut cinta. “Aku sepertinya kurang beruntung!” Demikian dia mengawali cerita.
Saat itu jam empat sore lebih sedikit, jam yang dingin untuk kota kecil di kaki gunung. Tetapi angin yang bertiup separuh basah tak cukup kuat menghentikan aliran cerita yang meluncur setengah suara dari mulutnya; sesekali kata-katanya bercampur asap dari batangan rokok yang dihisapnya dengan hikmat, seolah mampu menambah sakral senja.
“You see, bukankah itu artinya kurang beruntung?” Demikian dia memberi jeda usai menceritakan kisah pertama.
Ini kisah tentang dia yang jatuh cinta pada sahabat kecilnya, teman sepermainan yang lama menghilang untuk kemudian bertemu lagi pada kondisi yang lain. Pertemuan yang melahirkan percik aneh dan getaran hebat yang kemudian dengan senang hati dia simpulkan sebagai cinta.
Beberapa mimpi dibangunnya sendiri. Mimpi yang mungkin lebih tepat diberi nama harapan yang tak terungkap. Sambil bermimpi sembari mengumpulkan keberanian untuk bilang, “saya mencintaimu” atau “kau mau jadi kekasihku?”
Sebulan mereka bertemu. Oh tidak, mereka tetap bertemu sekarang, hanya saja waktu sebulan adalah hitungan ketika dia membangun mimpinya dengan penuh harap, sambil mengukur seberapa besar peluang mimpi berubah menjadi realita.
Ya, hanya sebulan. Karena setelah sebulan, ketika keberanian mendesak suara hati menjadi kata-kata, ketika keyakinan akan mampu mengulang kisah masa kecil menjadi agape sudah terbangun, semua tiba-tiba terbungkus dalam satu kata: terlambat. Teman masa kecil telah jatuh cinta pada yang lain, bahkan sebelum dia memutuskan coklat ataukah bunga yang yang akan dia bawa untuk hari penting itu, untuk pujaan dari masa lalu.
Asap rokok bercampur kabut senja, cerita tak berhenti, masih tertutur setengah suara, hari tak lagi ramai.
“You see, bukankah itu artinya kurang beruntung?” Demikian dia memberi jeda usai menceritakan kisah pertama, sebelum beralih ke kisah selanjutnya.
Teman masa kecil telah bahagia. Meski pahit, semua harus kembali seperti semula, sama sebelum bertemu dengannya dan membangun mimpi yang berujung suara teman kecilnya berujar, “hei, aku sudah pacar and bla bla bla…. Dia tak mendengar lanjutan curahan hati tak terduga itu, karena di kepalanya telah ada pilihan baru selain coklat atau bunga; PULANG.
Dan kisah yang dia tuturkan berikutnya adalah tentang masa sebelum bertemu teman masa kecilnya. Kuliah, punya pacar, berbagi kasih dengan wajar, tetapi berujung datar. Bukan karena tak ingin mengajaknya menikah. Semua terasa sangat pas, tidak berlebih memang tetapi juga tak ada yang kurang. Pas. Dan bukankah itu adalah alasan yang tepat untuk membangun sebuah komitmen? Fit In. Komunikasi terbangun mengalir, ada yang kurang jika sehari tak sempat bilang “miss u”, beberapa pertengkaran kecil terlewati dengan santai, kejujuran menjadi modal utama, perhatian menjadi kata kunci.
Sayang, mereka tak seiman. Agama mereka berbeda. Tak ada yang mau mengalah, tak ada yang mau menyembah Tuhan yang baru. Keduanya sepakat mengikat itu sebagai kisah masa lalu dalam hidup mereka. Putus. Sebagian merasa itu adalah alasan paling sederhana untuk memutuskan sebuah hubungan yang pas. Berhenti karena tak seiman. Terlalu sederhana, tetapi tidak bagi dia, dan tak ada satupun protes yang mampu melumerkannya. Baginya ini soal prioritas, dia atau Tuhan.
“Sejak dulu, saya memang kurang beruntung!” Demikian dia berujar setengah suara, setelah yakin bahwa kisah bagian ini telah selesai.
Hening. Taman kota sesepi biasanya. Senja menua. Siklus hari yang tak istimewa. Senja pasti menua, sekuat apapun kau memohon agar ada di detik yang sama, tetapi setelah senja selalu ada malam, waktunya kembali ke rumah jika tak ingin dipeluk kelam.
Sebatang baru rokok kembali dinyalakan, dihisap sepenuh hati, asap dibiarkan lebih lama dari biasanya menodai paru-paru, dihembuskan perlahan. Ritual itu terulang beberapa kali, sebuah penjelasan betapa dia memerlukan kekuatan lebih untuk menuturkan kisah terbarunya.
Dia jatuh cinta. Jauh lebih dalam dari yang pernah singgah. Dia jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Dan keyakinan telah menghantarnya ke titik bernama kesimpulan, ini adalah jatuh cinta terbaik yang pernah ada. Entah dari mana kesimpulan itu muncul. Tak ada yang tahu barometer apa yang dipakai untuk mengukurnya, toh ini bukan soal rasio tetapi rasa. Rasa hanya mampu diukur oleh rasa.
Dia jatuh cinta, tak bertepuk sebelah tangan. Gayung bersambut. Bagai lagu, dia terpilih di antara ribuan harmoni nada bersyair, merdu meluluhkan segala ragu. “Aku sangat yakin dengan yang sekarang ini” katanya masih setengah suara, menegaskan di tengah cerita masa kini. “Bukan sekedar fit in, tetapi perfect fit” lanjutnya. Tetapi lanjutan kisahnya tak seirama dengan prolog bagian ini.
Karena dia lalu bertutur tentang sesuatu yang mengganggu. Kisahnya yang baru kini ternoda cemburu. Kekasihnya kini bukan tidak mencintainya. Hati kecilnya pun tahu, kekasihnya kini mencintainya dengan sempurna yang pas. Tetapi beberapa waktu sebelumnya, kekasihnya entah kenapa tiba-tiba bertutur tentang cerita manisnya bersama kekasihnya di masa lalu. Tak ada yang salah dalam ceritanya, juga tak tersirat dalam bahasa wajahnya bahwa dia, kekasihnya itu ingin kembali pada masa lalu. Sama sekali tidak. Dia hanya bercerita, bercerita dengan ceria. Maka meski diserang cemburu yang hebat, tak ada niatan untuk menghentikan cerita kekasihnya itu. Dia mencoba menjadi bijak dengan berpikir, “Kadang kita memang harus bercerita saja dan tak perlu berpikir apakah orang lain ingin mendengar cerita kita atau tidak. Kita hanya perlu bercerita dengan jujur dan tak perlu peduli, apakah yang mendengar cerita kita bersuka atau malah berduka. Kita bercerita dan bahagia.”
Dan lihatlah, kekasihnya bahagia saat bercerita. Adakah yang lebih mulia daripada merasakan apa yang dirasakan oleh kekasih kita dengan jumlah dua kali lebih banyak? Maka, kekasihnya bahagia dan dia harus dua kali lebih bahagia. Tetapi hati memang punya bahasanya sendiri. Tak ada mekanisme kontrol yang cukup untuk mengendalikannya, dan cemburu tetap saja cemburu. Lalu apa yang harus dia buat? Situasi seperti ini terlalu sulit. Cemburu tetapi harus terlihat dua kali lebih bahagia. Tak ada satu orangpun yang ingin ada dalam situasi seperti ini, juga dia. Maka beberapa kekuatan dikombinasikan sekaligus. Rasio, rasa, dan alam bawah sadar. Hasilnya lumayan. Dia akhirnya sampai pada bagian ini.
Begini caraku mencintaimu. Mendengarmu bercerita tentang dia tetapi menutup telingaku rapat. Aku tak mau mendengar apapun tentang masa lalumu, tetapi sepertinya kau bercerita dengan ceria. Aku tak ingin cemburu; -semoga kau tahu bahwa aku selalu cemburu dengan kisahmu dengan dia-, tetapi tak mau mengganggu ceria ceritamu. Begitulah aku mencintaimu; sesederhana itu, dan akan tetap seperti itu. Teruslah bercerita, aku dua kali lebih bahagia jika kau bahagia karena telah bercerita, tetapi maaf aku menutup telingaku rapat.
“Sekarang aku merasa beruntung telah menjadi sesederhana ini,” katanya mengakhiri cerita sore itu lalu beranjak pergi.
Ditinggalkannya taman itu, juga bangku tembok tempatnya duduk dan bercerita. Tak ada yang lain di sana, hanya dia dan taman yang sepi dan bangku yang kini kosong. Dia bercerita pada angin senja dan berhenti saat malam tiba dan bahagia.
Sumber : Kompas Indonesia
 Kamila Andini, putri sineas Garin Nugroho dipercaya untuk menyutradarai film tentang laut Wakatobi dan kehidupan masyarakat Suku Bajo, Sulawesi Tenggara. Dia akan memimpin pembuatan film yang didanai oleh Pemeritah Kabupaten Wakatobi bekerja sama dengan Yayasan SET dan WWF-Indonesia.
Kamila Andini, putri sineas Garin Nugroho dipercaya untuk menyutradarai film tentang laut Wakatobi dan kehidupan masyarakat Suku Bajo, Sulawesi Tenggara. Dia akan memimpin pembuatan film yang didanai oleh Pemeritah Kabupaten Wakatobi bekerja sama dengan Yayasan SET dan WWF-Indonesia.