

BAIKLAH. Awal kisah kita khayalkan saja bahwa kita semua sedang berada dalam sebuah pergelaran wayang besar. Dan dari sepasang garis bibir yang gemar melantunkan sajak dan prosa, selarik cerita tentang lakon usang kututurkan:
Di sebuah desa yang kering kerontang, penduduknya hidup dalam penderitaan. Padahal desa itu adalah bagian dari negara yang –katanya- kaya dan makmur. Tapi, tanahnya keropos dan retak menganga akibat musim kemarau yang panjang. Sungai-sungai yang tadinya penuh air, kini disulap menjelma lumpur yang membatu. Sumur-sumurnya dangkal dan gemerincing. Bahkan tanaman mereka layu dan mati. Hidup dalam kekurangan sumber kehidupan sangat menyesakkan dada, bikin hati alergi. Membuat mereka saling berebut dan tak jarang saling bunuh-membunuh dimana yang kuat akan menginjak-injak yang lemah.
Hingga suatu hari, seorang penduduk menyarankan agar diselenggarakan sebuah pergelaran wayang sebagai ritual untuk meminta hujan dari langit. Dan semua warga menyepakati.
Panggung didirikan. Segala sesuatu yang diperlukan diletakkan pada tempatnya. Latar yang bisa diganti-ganti, beberapa gunungan, sebutir matahari, bulan, beberapa bintang, bukit-bukitan, pepohonan, anjing, kereta kuda dan beberapa senjata untuk para wayang.
Para wayang dikeluarkan dari almari, dan Dalang sudah bersiap bersama para pesinden beserta pengiring. Seluruh penduduk, laki-laki dan perempuan, dari anak-anak hingga manula pun telah berkumpul di depan panggung. Pertunjukan wayang segera dimulai.
Lalu para wayang itu masuk ke dalam biliknya. Jemari lentik di ujung selendang; menari sesaat dan lunglai di lantai. Mereka dipaksa menari, mereka tak mengerti.
Pohon-pohon menjulang tinggi di tepi danau. Ada desau angin berpusar. Di sana -di antara semak-semak dan bunyi jangkrik- Kunthi seolah kena hipnotis, lalu disetubuhi oleh empat lelaki yang tidak dikenalinya. Mereka datang sebagai angin, lalu menghilang sebagai cahaya.
Sementara itu, di ruang tahta Astina, Pandu –suami Kunthi- yang dalam dirinya melekat kutukan mandul terpaksa menikah lagi dengan Madrim, yang juga tak pernah bisa dibuahinya.
Adegan berikutnya, Sundari yang tak dikaruniai anak harus rela dimadu Abimanyu dengan Utari. Tubuh Shinta pun dibakar oleh Rama hanya sekedar untuk menguji kesucian dan kesetiaannya. Bahkan Anjani, yang sangat cantik, harus tabah meski hamil tanpa suami, dan wajahnya berubah menjadi kera, serta anaknya menjadi kera pula -Hanoman. Malam mulai menghitam. Bulan hampir mencapai titik jenuhnya, pertunjukan wayang itu belum juga usai. Harapan yang dipinta pun tak kunjung datang memberi kabar.
Tak lama kemudian, petir mulai menyambar-nyambar di sebelah timur desa. Membelah gelapnya malam dan menghancurkan pucuk pohon palma di pekarangan milik penduduk. Trembesi patah dan tumbang. Sontak seluruh penduduk yang menonton pagelaran wayang lari lintang pukang. Jerit ketakutan dan lolong kematian berloncatan. Aroma kamboja ditebarkan. Menggema membentur dinding gunung, dan merayap di awan-awan hitam. Bulan setengah lingkaran lenyap secara misterius. Kepekakan yang menyakitkan membuat orang-orang menutupi telinganya. Perempuan dan anak-anak berlarian. Sebagian menuju rumah masing-masing. Mengancing pintu dan jendela rapat-rapat. Sebagian lagi masih kepanikan mencari tempat sembunyi yang aman. Kecuali Dalang yang tetap duduk di bantalan singgasana dan menegaskan hukumnya: “Wayang akan tetap diam jika tak ada Dalang yang menggerakkan!” Latar berganti. Seperti bidang catur berhias bebukitan gersang. Matahari digantung terjepit di antara bukit. Suara-suara tabuh kendang terdengar keras bergemuruh. Bidak-bidak catur Klan Pandawa berhadapan dengan Klan Kurawa. Kini perang Baratayudha kembali bergolak. Darah bersaudara berceceran, tumpah ruah dimana-mana.
Beberapa waktu, medan perang Kuru tinggal lapangan penuh bangkai. Bau busuk terbentang. Rasa cemas terapung ke kaki langit. Ribuan anjing ajak melolong, mengaum, mengais. Selebihnya cuma erang sekarat para prajurit, di antara sisa kereta dan senjata yang patah. Warna di sana hanya darah. Anyir. Tak akan ada lagi perbuatan kepahlawanan. Jauh sebelum perang itu terjadi, telah ada penyimpangan dimana hak Destarastra sebagai pewaris tahta Kerajaan Astina diambil alih oleh Pandu hanya karena Destarastra mengalami kebutaan. Episode yang selalu berulang dari abad ke abad dalam segulung cerita tua. Menyedihkan!
Tapi, Dalang terus melantunkan kidung bagi wayang-wayangnya. Suara gamelan dan lantun gemulai suara pesinden terus terdengar merdu. Para penabuh kendang, gong, boning dan peniup suling pun masih penuh semangat membara melanggengkan tahta Dalang dan mengiringi lakon usang para wayang.
Langit makin menghitam sekam. Gelegar guntur masih terus menakut-nakuti warga yang berlarian. Di tengah-tengah hiruk pikuk itu, tiba-tiba aku mengalami semacam bayangan eidetik. Aku tuangkan seluruh gelisah pada lakon yang enggan berontak. Kutunggu waktu hinggap dan memberikan keajaiban; angin mereda dan mengusap semua penderitaan yang tersisa di kantung mata. * “HUH, membosankan! Menyakitkan!” “Jangan menangisi takdir…” “Tapi, diam membunuh hidup kita. Lihat! Dongeng-dongeng Dalang menutup mata kita. Mengendalikan pikiran kita.” “Jangan berkata seperti itu. Kita akan berdosa pada Dalang. Dialah sumber kebenaran, dialah agama, dialah sang moral. Tak ada satu pun dari apa yang kita lakoni ini luput dari kendalinya. Karena dia mahatahu dan mahakuasa. Semua harus mengikuti hukumnya; Hukum Dalang!” “Ah, kamu terlalu kaku sebagai wayang. Kita sudah memasuki abad ke-30. Kidung yang dilantunkan oleh Dalang telah membentuk sejarah dan peradaban kita -para wayang. Kita terlalu menggantungkan peran kita padanya. Kita telah dikendalikan oleh kidung itu, kita semua dibuatnya berperang, membunuh saudara dan sanak keluarga, saling menumpahkan darah hanya untuk menghibur dirinya dan untuk pengakuan atas dirinya.” “Setuju! Tidakkah kalian pernah berpikir, kenapa Dalang kita harus berjenis kelamin laki-laki?” “Ah, kamu ini perempuan jangan terjebak dengan tipu daya feminisme itu. Kalian tidak lain hanya sekedar sandal jepit. Sakti, tapi berdomisili di kaki.” “Sekedar tahu-tahu tempe, asale mung saka dhele, kabeh-kabeh mbutuhake..”1) “Hei kalian para pahlawan. Jangan lagi menyakiti hati perempuan!” “Hahaha. Kenapa? Mau berperang? Kami yang terkuat dalam sejarah. Perempuan-perempuan cantik ini selalu berada di pihak kami meski bagaimana upaya kalian merebutnya.” “Sudah, cukup! Kita sudah berabad-abad berperang. Saling bunuh-membunuh. Dan selalu mempertengkarkan persoalan yang sama. Tidakkah kalian sadari kita seperti terjebak dalam sebuah desain permainan besar?” “Tidak! Kalian para tokoh antagonis memang sudah ditakdirkan untuk kalah. Tidak perlu kalian melakukan diplomasi seperti ini.” “Tidak. Tidak! Ini bukan keadilan. Kenapa Dalang selalu melantunkan bahasa seperti sajak dan prosa? Bukankah itu basa basi dan sulit dimengerti? Kita tidak boleh terjebak di dalamnya. Kita harus keluar dan menentukan takdir kita sendiri.” “Sajak dan prosa itu adalah kebenaran mutlak. Itulah Undang-Undang Dalang yang menjadi petunjuk hidup kita. Kita harus mencintainya.” “Itu salah! Mencintai kebenaran akan menjerumuskan kita pada fanatisme yang menenggelamkan kita pada kecintaan buta atas kebenaran itu sendiri. Betapa kita telah kehilangan kekritisan yang tajam, ketika kita telah mencintai kebenaran hanya dari satu tafsiran. Celakalah, jika kebenaran telah berhenti pada titiknya. Sebab, ia bukan lagi sebagai kebenaran.” “Kita harus bergegas menuju taman jalan setapak bercecabang -di sebuah kota- di mana kabar-kabar adalah tafsir yang tertunda, di mana Dalang hanya sebuah kata sebelum kita amnesia.” “Betul. Jika Dalang telah mencampuri kebebasan dan kreatifitas kita, maka dia adalah tiran. Dan suatu tiran yang mahakuasa dan mahatahu tidak berbeda dengan diktator dunia yang membuat segala sesuatu dan semua orang menjadi boneka robot dalam tangan mesin yang dikendalikannya.” “Kalau kau merasa kita tidak boleh cinta pada kebenaran, lalu kenapa kau sendiri berkata bahwa pendapatku ini salah? Apakah pendapatmu itu adalah kebenaran?” Semua wayang terdiam. Tak ada kata. Tak ada bisikan. * KINI angin bertiup begitu kencang di antara sambaran petir dan gelagar guntur. Merobek beberan layar berwarna putih tepat di tengah-tengahnya. Atap panggung yang terbuat dari seng berkarat, bergrombyangan. Satu dua keping terbang, entah jatuh di mana. Kumbakarna tercerabut dari tancapannya. Tubuh Wibisana hancur bersama kebijaksanaannya. Bagong dan Petruk patah tubuhnya menjadi dua. Para raja, permaisuri dan beberapa gunungan yang tertancap kokoh pun kini tak terlihat lagi. * “KALAU begini ‘kan kacau!” “Kepada siapa kita akan bertanya?” “Langit!” “Apa yang akan kau tanyakan? Langit sedang geger. Para Dewa kehilangan wibawa!” “Kita coba tanya ke..” “Mega!” “Apa petir tidak marah?” “Oh, ke laut?” “Laut? Di sana juga sudah tercemar Uranium dan Plutonium!” “Matahari! Siapa tahu bisa menjawabnya!” “Ke bulan?” “Kita kembali ke angin atau cahaya!” “Kita kembali ke mana?” “Ke asal. Kembali ke Dalang!” “Tidak! Kita harus membunuh Dalang. Kita harus mengambil kesempuranaan kita dengan membunuhnya. Apa yang selama ini menjadi kebenaran dan moral menurut kita, harus kita verifikasi.” “Bagaimana caranya?” “Dalang harus kita bunuh!” “Nekad benar!” “Lalu, kita hanya akan diam menunggu takdir kita datang menjemput dengan menggantungkan peran kita padanya?” “Kau akan melanggar Undang-Undang Dalang, melanggar Hukum Dalang. Dan itu makar namanya!” “Makar? Boleh-boleh saja!” “Aku ingin berkata bahwa ini salah!” “Salah?” “Kau menyalahkan duniamu?” “Tidak. Hanya sekedar membuka kemungkinan.” “Apa itu? Kau bermimpi? Ini dunia wayang, panggung sandiwara! Di sini tidak ada kemungkinan selain kehendak Dalang.” “Dunia busuk! Ini apa? Mulai hari ini, kita harus memutuskan, apakah kata ‘Dalang’ dan kidung-kidung candunya itu masih memiliki makna bagi kita untuk saat ini. Kita harus menjadi dalang bagi diri kita sendiri!” * ANGIN puting beliung kini berpusar, bagai tiang utama rumah-rumah ibadah yang bulat melonjong dan kokoh. Berpokok pada bumi dan berujung di langit. Meliuk-liuk seperti penari ular. Lincah, tapi menakutkan. Gerakannya menggores kulit bumi. Menyeramkan. Separuh panggung ia hancurkan hingga berantakan segala yang ada di atasnya. Semar dan Bathara Guru pun dibawanya. Gatotkaca kini jatuh ke tanah. Tubuhnya penuh lumpur. Tak berdaya. Terinjak-injak oleh penduduk desa, yang biasanya justru membanggakannya. * MALAM makin membeku, Dalang mulai panik. Bayangan eidetik itu semakin menggelinjang: Krepa –yang dikenal sebagai sosok pendiam dan penurut- tiba-tiba berdiri di tepi panggung. Lengannya menggenggam sepucuk pistol dan mengacungkannya pada sesuatu di hadapannya. Sukesi –yang berhasrat meraih Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu2)- pun keluar dari tugunya dan dikibaskannya sampur. Sepercik memori kembali melayang pada episode angkara di ujung malam, saat-saat ketika dia didalangi oleh sesuatu untuk bersetubuh dengan Wisrawa yang menjadi penyebab lahirnya klan Alengka. Dan Sastra Jendra pun gagal diraihnya.
Wajahnya begitu murka. Belajar dari seluruh pengalamannya, Sukesi berekesimpulan bahwa untuk meraih Sastra Jendra hal pertama yang harus dilakukannya adalah membunuh Dalang yang selalu menggagalkannya pada setiap pementasan. “Kali ini harus kuraih! Tak ada lagi semboyan; swarga nunut, neraka katut!3) Tak ada sesuatu pun yang boleh menggagalkanku!” Serunya dalam hati. Dirampasnya sepucuk pistol dari genggaman Krepa. Dari sudut sebelah kiri panggung, busur Arjuna menegang dalam genggaman Indrajit, bersiap melepaskan anak panahnya. Di belakangnya, para tokoh antagonis dalam pewayangan telah siap dengan senjatanya masing-masing. Sesaat kemudian, cahaya petir menyalak di kegelapan panggung. Para wayang yang tersisa telah sepakat satu kata yang diberi banyak tanda seru: “Tembaaaaaaakk!!!!!!”
Sesuatu berjatuhan di atas panggung. Tragis. Beberapa waktu, petir hilang cahayanya, guntur raib suaranya. Suara gamelan dan lantun gemulai suara pesinden tak lagi terdengar. Tiga pesinden telah lari, sambil mengangkat kainnya setinggi paha. Para penabuh kendang, gong, boning dan peniup suling pun tak ada lagi. Apa yang kemudian terjadi? Sontak seluruh wayang tersungkur; tubuh mereka tergeletak pasrah di atas panggung, tak bergerak dan mati. * GERIMIS lalu turun rintik-rintik. Pintu-pintu rumah penduduk mulai terbuka. Mereka berlari keluar menuju pekarangan. Laki-laki, perempuan dan anak-anak berjingkrak-jingkrak. Suami istri dan orang-orang tua saling berpelukan. Mereka berkumpul kembali di depan panggung, seperti saat mereka menonton pagelaran wayang sebagai persembahan untuk minta hujan. Tersirat rasa suka cita pada wajah-wajah mereka menyambut air yang mengucur dari langit. Permohonan hujan telah terkabulkan. Gerimis pun kini berubah jadi hujan lebat. Bumi yang kering kerontang mengeluarkan asap hangat. Tak lama kemudian basah dan becek. Warna putih debu menjadi hitam berair.
“Hujan. Akhirnya engkau memberi kabar di tengah buaian daun musim gugur dan hawa angin bersisik peluh. Biarkan barisan airmu mengelus hiruk pikuk beraroma kamboja, menautkan tanah-tanah yang gemerincing dan menganga. Suburkan semangat hidup kami, dan hilangkan angkara murka di antara kami. Isilah sungai-sungai yang lumpurnya telah lama membatu, seperti hati kami. Basahilah. Usirlah kepedihan yang berkepanjangan. Meleburlah ke dalam segala dan rangkum seluruh peristiwa. Biarkan lidah sejukmu menjilati tubuh kami. Tanah kami. Tanaman kami yang merasa tak nyaman diperkosa situasi,” ujar seorang penduduk di tengah euforia itu.
Lelaki itu sepertinya sesepuh desa yang memimpin acara ritual permohonan hujan. Dupa di tangannya diacung-acungkan di atas kepalanya. Asap mengepul membuat bayang-bayang tak terbaca. Membuka berlembar-lembar kemungkinan. * DARI kejauhan, di sebuah panggung yang lebih besar, AKU yang sejak tadi sedang bermain-main dengan wayang-wayangku, hanya tersenyum menyaksikan prosesi itu. Aku melantunkan kidung metaforis lirih, “Aku takkan merubah nasib suatu kaum, jika bukan mereka sendiri yang mengubahnya.” Itu janjiku dulu. Karena wayang tanpa Dalang ibarat Dalang tanpa wayang. (*) -hz-
Catatan: 1) tahu-tahu tempe, asale mung saka dhele, kabeh-kabeh mbutuhake = tahu-tahu tempe, asalnya cuma dari kedelai, tapi semua orang membutuhkannya. (Potongan lagu “Tahu-Tahu Tempe” karya NN) 2) Secara etimologis, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu berarti: Sastra = Ilmu Jendra = Bisa dipahami sebagai kemuliaan atau sesuatu yang bernilai namun sifatnya immaterial, sesuatu yang samar. Bisa pula dipahami sebagai rongga dada, yang kerap dipahami sebagai gerbang menuju ‘rasa sejati’. Hayu = Cakap, indah Ning = Bening Rat = Semesta alam Pangruwating = Yang mampu membersihkan, mentransformasikan Diyu = Raksasa 3) swarga nunut, neraka katut = ke surga ikut, ke neraka turut.













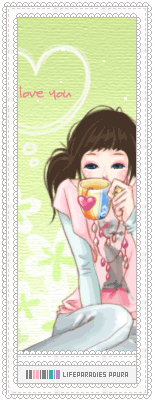
0 komentar:
Posting Komentar