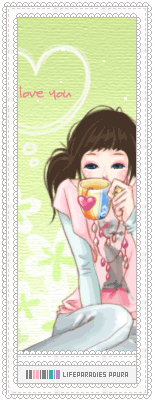"Selalu saja seperti itu, bicara soal warna sambil bercumbu, pikirku
sambil menikmati nafasnya dan memperhatikan detak jantungku sendiri"
"Selayaknya ini bukan puisi," katamu saat mendorong secarik kertas
itu kehadapanku. kertas itu berhenti dengan rapi dalam jarak yang tepat
sekian senti dari cangkir kopiku yang mengepulkan asap dan aroma pagi
yang kita kenal baik.
"Aku hanya ingin mengibaskan mendung yang
menggantung di langitmu. bukankah sudah terlalu lama dia mengganggu
karena enggan menjadi hujan?" Katamu lagi.
Aroma pagimu selalu
saja lebih segar daripada milikku. Wajah cerahmu yang tercukur licin
memantulkan sinar matahari yang begitu muda mengecup langkah pagi yang
ringan membuka pintu hari. Sementara aku, selalu saja merasa diriku ini
masih terus-terusan betah duduk dalam waktu seperempat malam, menarik
selimut subuh dan bersikeras gelap masih menyertaiku. Ah, kamu kira
semua itu mendung? Padahal bagiku semua itu adalah selimut yang nyaman.
Aman. Menentramkan. Terbebas dari tanggungjawab. Boleh bermain dalam
mimpi. Ah, bagimu semua itu mendung?
"Bacalah." Katamu, dan
matamu, yang tenang setenang ombak saat riak angin lembut membantunya
menggempur pantai membuatku tak tega membiarkan kertas itu terdiam di
sana. Matamu itu nyaris tosca bagiku. Nyaris begitu dekat dengan langit
yang pernah kubiarkan menyentuh bumiku. Sekilas aku tersenyum
mengingatnya dekatku pada suatu sarapan pagi yang rasanya sudah
berabadabad silam terjadinya, saat itu aku Cleopatra dan dia, Marc
Anthony.
"Aku suka ungumu," Kata Laki-laki Langit Toscaku,
berbisik di telingaku sambil menciumi batang leherku dan menurunkan
kerah kemeja unguku. Tangannya hangat bermain-main pada kancing bajuku,
seakan-akan jari-jemarinya sedang berdialog, kancing yang mana yang akan
mereka buka lebih dahulu.
Selalu saja seperti itu, bicara soal
warna sambil bercumbu, pikirku sambil menikmati nafasnya dan
memperhatikan detak jantungku sendiri. Kami sedang berada di antara
sepiring puisi sepasang pengantin baru dalam bulan madu yang serupa
deras ombak mengalir seirama angin dan hujan saat musim monsoon tiba.
Puisi-puisi
puting beliung dalam belitan gemuruh dan desakan keinginan paling
mendasar yang kami santap pagi itu. Lalu kami teguk segelas besar
kupu-kupu tosca dalam gelembumg soda sehingga dalam perut kami berdua
ada ribuan kupu-kupu menarikan tarian mereka, bergelombang-gelombang
sensasi yang aku rasakan dari setiap teguk, memenuhi degup hingga penuh
dan aku mabuk dirinya seperti dirinya mabuk diriku.
Hanya saja.
Tak ada pesta yang tak usai. Tak ada tarian yang tak selesai.
Ternyata,
kupu-kupu tidak hidup sampai selama-lamanya. Mereka rebah satu demi
satu. Tertidur, pingsan, mati? Entah. Mereka hanyut dan hilang dari
dalam sistem, eforia itu perlahan menepi. Lalu, senyap datar
beringsut-ingsut datang mengisi celahnya, hidup menjadi sebuah
kebiasaan, bercinta menjadi semacam kewajiban, bahkan kadang merupakan
sebuah kematian yang monoton, entah dia yang mati atau aku yang mati,
atau dua-duanya mati sebelum pertempuran. Lalu, suatu pagi, aku bangun
dan dia pergi. Sepucuk surat, menjadi penegasan bahwa yang namanya cinta
itu stempelnya bukan sampai maut memisahkan kami, melainkan sampai tak
ada lagi kupu-kupu dalam gelembung-gelembung soda itu.
"Hei,
bangun cantik, jangan mimpi lagi." Kau menjentikkan jarimu di depan
wajahku. membangunkan aku dari mimpi tentang kemarin-kemarin yang
merupakan detik-detik usang. Aku memandangmu dengan rasa terima kasih,
yang sengaja kubiarkan menetap lama, jatuh tepat di anak matamu. Kita
beradu pandang, sekian detik berlalu menghentak menuju menit, kubiarkan
tatapanku berlabuh padamu, menepikan sampan-sampanku dan mencoba
menemukan sesuatu tanpa perlu merasa sangat ingin. Bagiku, sejauh ini,
adalah soal eksplorasi belaka, kemungkinan selalu menyenangkan untuk
ditelusuri. Siapa tahu, mungkin saja memang di sana ada pengganti harta
karunku? Entahlah. dan manik matamu bergerak, mengerjap, sebuah isyarat
yang kukenal baik dari sekian banyak pertemuan, matamu perlahan berusaha
mengalihkan pandangan ke lain tempat.
Aha!, di dalam relung
hatiku aku bersorak, selalu saja seperti itu rasanya ketika menang adu
tatap. Ah Lelaki Pagi berdasi kuning kecoklatan berselempangkan
garis-garis abu-abu di atas kemeja abu-abu mudamu yang licin dan cermat
(selalu saja aku ingin bertanya, siapa yang menyetrikakannya untukmu?),
kau jengah saat kupandang sedemikian rupa. Lelaki pagi. Ya, ya, itu
dirimu, Lelaki pagi, sepagi matahari muda yang mengecup wajah bumi
dengan sekecup ringan dan harum nafasmu sesegar bau mulut setelah
berkumur dan sikat gigi. benarbenar segar. Dan sekarang kau jengah, saat
mata milik malam ini menghujanimu dengan kecupan dari dalam jiwa.
Sekilas pipimu merona sebelum kau memberitahuku bahwa kau sudah
memanggil seseorang masuk dalam lingkaran ajaib milik kita. Ah. Mengapa
harus begitu?
"Tidak keberatan kan?" Tanyamu dengan suara rendah
dan lembut seraya tanganmu menyeberangi ruang antara kita lalu menyentuh
ringan tepi jemariku. "Tanpa ijinmu, aku mengajak Maya makan pagi
bersama, sebab kita harus membicarakan proyek buku kita bersama-sama.
Maya adalah ilustrator paling keren yang aku kenal. Aku mempercayainya.
Dan satu hal lagi. Aku sudah secara lancang, mengirimkan draft tulisan
itu kepadanya. Disela lunch, kemarin, kami sudah bertemu dan menakjubkan
sekali hasil interpretasinya, karena itu aku berani mengajaknya pagi
ini untuk bertemu denganmu. Ini sebuah kejutan." Kau mengangkat jemarimu
dari atas jemariku dan tersenyum lebar seperti bocah kecil yang bangga
karena berhasil membaca satu kalimat penuh tanpa terbata-bata. Mengapa
kau angkat jemarimu dari tepi-tepi jemariku? Aku masih ingin persentuhan
itu berjalan sedikit lebih lama.
Aku tersenyum tipis, memikirkan
seandainya saja kamu bisa membaca pikiranku saat ini. Lelaki pagi
berdasi kuning kecoklatan dihiasi garis miring abuabu, bolehkah aku
mengecupmu? Tanya mataku. Kau sepertinya mencoba setengah mati untuk
menjadi kekasihku setiap kita sarapan pagi. Kini kau sudah melangkah
jauh ke dalam hidupku. Hei, kau bahkan bisa kulamar menjadi suamiku
suatu saat nanti kalau keadaan kita tetap seperti ini.
Tapi, tunggu dulu.
"Maya?
Aku ingat nama itu pernah dihubungkan dengan namamu, kan? Hmm... apakah
dia ini Maya yang sama dengan Maya mantan kekasihmu?" Tanyaku, berusaha
mengatakannya seenteng tisu yang baru saja kukeluarkan satu lembar dari
bungkus mininya. Dan kamu, Laki-laki Pagi, nampak salah tingkah.
"Hanya
rumours," katamu singkat seraya sedikit mengernyitkan keningmu, lalu
berkonsentrasi pada sepiring nasi goreng yang pagi ini menjadi
pilihanmu, sementara aku masih meniup permukaan sup krim panasku di
dalam mangkuk lebar yang nyari menelan wajahku, sambil mengulang
ucapanmu, "hanya rumours?", dan kamu mengangkat bahumu sedikit, ujung
bibirmu sebelah kananmu terangkat sedikit juga, sambil menjawab ringan,
"rumours yang sama sekali tidak penting."
Sialan kau! Mengapa
gerakan facial kecil itu begitu menarik kelihatannya? Tiba-tiba saja aku
menyadari bahwa ada sebuah sensasi yang berbeda. Nampaknya aku,
perempuan teman sarapan pagimu ini sedang dilanda gelombang yang
berbeda. Sedang menjadi buih-buih di atas ombak-ombak dari sesuatu yang
sudah lama tidak kurasakan. Diam-diam aku mencuri pandang ke arahmu dan
terpesona sendiri dengan sesuatu di dalam diriku. Keinginan untuk
memagari waktu-waktu kita tanpa interupsi, apapun bentuknya, atau lebih
tepatnya siapapun bentuknya. Aku mendadak jengah dengan apa yang aku
rasakan.
Tepat di saat itu Maya melambai cantik, bagai dua tetes
madu manis yang menetes tanpa sengaja di antara kita, "Selamat pagi,"
katanya berdenting dalam sebuah notasi nyaris sempurna, perempuan yang
dibalut busana kasual itu masuk dalam orkestrasi pagi hari ini, menyatu
sempurna dengan pagi milik Lakilaki Pagi itu, seakan dialah yang telah
menyetrikakan bajumu dan mengenakan dasi itu ke sekeliling kerah
lehermu.
Dan kamu Lelaki Pagi, kamu tersenyum lebar, berdiri
menyambutnya, mengecup pipinya kiri dan kanan sebelum menyeretkan kursi
untuknya dan mempersilahkannya duduk. Kusadari bahwa kita kini bertiga.
Tiga, sebuah angka yang ganjil kan? Ufh! Sarapan pagiku mendadak beku.
Aku tersenyum ke arahnya dengan berkilo topeng memberati seluruh syaraf
wajahku. Ingin rasanya aku pergi saja dan menyerahkan segala keputusan
ke tanganmu, bukankah kamu sudah lebih dahulu memutuskan segala-galanya,
jadi, silahkan, teruskan saja! ingin juga rasanya kutuangkan kopi ke
atas kepalamu. Dasar lakilaki!
Tapi, tunggu dulu.
Mendadak
aku berhenti dan merasa ingin menendang bokongku sendiri. Luarbiasa
konyol! Ya, aku yang konyol. Jelas-jelas, amat sangat konyol! Bukankah
baru lima menit yang lalu semua ini kuanggapa sebagai sebuah perhatian
yang mendebarkan dan menghangatkan hati? Arrrggghhh... ingin kubenamkan
wajahku ke dalam mangkuk sup, di saat itu kulihat asapasap tipis naik
kembali dari permukaan sup. Aku jadi kepingin sekali tertawa,
menertawakan kebodohan itu. Ayolah SN, tak ada alasan untuk cemburu, aku
membujuk diri sendiri. Mendadak pula aku ingat kertas yang tadi kamu
berikan kepadaku, belum juga sempat kubaca. "Selayaknya ini bukan
puisi," katamu tadi. Kalau begitu, apa kirakira? Kulipat kertas itu lalu
saat kuselipkan ke dalam tas tanganku, aku menangkap matamu
memandangiku dengan sinar mata yang tak mampu kutebak sementara suara
Maya mengisi udara disekitar kita, menceritakan tentang kemacetan yang
harus ditembusnya sepanjang jalan menuju ke tempat pertemuan ini. Ah,
pagi selalu berselingkuh erat dengan kemacetan di Kota Besar ini.
Baiklah,
kututup sesi tanya-jawab dengan diri sendiri lalu bergabung dengan
kalian. Maya menyalakan laptopnya, meletakkannya pada posisi yang paling
tepat sehingga ia dapat mempertontonkan gambargambar yang telah
dibuatnya untukku, untuk kita, sekaligus menjelaskan detil-detil yang
perlu. Harus kuakui aku terpesona, dia bisa menangkap persis seperti
yang kuinginkan. Hanya satu saja kekurangannya, mengapa musti Maya? Di
saat itu, kurasakan tanganmu memijat lembut tengkukku, baru kusadari
bahwa kamu telah berdiri tepat dibelakangku. Ah, aroma aftershavemu
membuat aku memutuskan untuk mengecup bibirmu. Aku berjanji akan
melakukannya. Nanti malam, dalam mimpiku.
Bio singkat pengarang: Ge Siahaya, domisili di Jakarta, aktif menulis di blog Kampung Fiksi:
http://kampungfiksi.com/, sudah menerbitkan antologi cerpen.